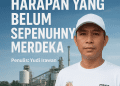Ketika Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 pada 16 Oktober 2025, gema tepuk tangan terdengar di ruang publik. Dalam putusan yang monumental itu, MK menegaskan: masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di kawasan hutan dan berkegiatan bukan untuk kepentingan komersial tidak wajib mengantongi izin pemerintah untuk berkebun di dalam hutan.
Di permukaan, keputusan ini tampak sederhana — sekadar tafsir ulang atas norma izin berusaha di kawasan hutan. Namun di baliknya, tersimpan napas panjang perjuangan ratusan komunitas adat di seluruh nusantara yang selama puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang kriminalisasi.
—
Dari Peladang ke Tersangka
Sebelum putusan ini lahir, pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf b Lampiran UU 6/2023, sering kali dijadikan dasar hukum untuk menjerat masyarakat adat yang membuka ladang di wilayah nenek moyangnya.
Di Kalimantan Barat, seorang petani Dayak di Sintang, Yusri, pernah ditangkap karena dianggap membakar lahan untuk berladang, padahal ia menjalankan tradisi menugal — menanam padi secara bergilir sebagaimana dilakukan leluhurnya.
Di Sumatera Utara, komunitas adat Pandumaan-Sipituhuta pernah digusur dari tanah adat mereka karena perusahaan pulp mengklaim wilayah tersebut sebagai konsesi hutan produksi.
Di Papua, masyarakat Suku Awyu berhadapan dengan perusahaan sawit raksasa yang mendapat izin pemerintah untuk membuka lahan di kawasan yang secara adat mereka kelola selama ratusan tahun.
Kasus-kasus semacam itu menunjukkan paradoks besar: negara yang menjanjikan perlindungan bagi masyarakat adat justru sering menempatkan mereka sebagai pelanggar hukum di atas tanahnya sendiri.
—
MK Menarik Garis Etis
Melalui putusan ini, MK mencoba menegakkan keseimbangan. Negara memang memiliki kewajiban menjaga kelestarian hutan — tetapi perlindungan ekologi tak boleh mematikan ekosistem sosial dan kultural masyarakat adat yang justru telah menjaga hutan jauh sebelum republik berdiri.
MK mengoreksi tafsir sempit dari norma “setiap orang dilarang berkebun di kawasan hutan tanpa izin”. Kata setiap orang tidak boleh memukul rata masyarakat adat yang hidup turun-temurun dan tidak melakukan kegiatan komersial.
Putusan ini mengingatkan kita pada prinsip lex humanitatis — bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.
Dengan begitu, masyarakat adat tidak lagi harus berjalan di antara dua ancaman: kelaparan karena tak bisa bercocok tanam, atau penjara karena dianggap “merusak hutan negara”.
—
Kemenangan Bersyarat
Namun, perlu dicatat: kemenangan ini bersifat bersyarat. MK tidak membuka karpet merah bagi semua aktivitas di hutan atas nama adat.
Pengecualian hanya berlaku bagi komunitas yang benar-benar hidup turun-temurun di dalam kawasan hutan dan tidak berkegiatan secara komersial.
Artinya, masyarakat adat yang menjadikan aktivitasnya sebagai usaha besar — misalnya perkebunan sawit rakyat berskala luas — tetap harus tunduk pada izin dan regulasi kehutanan.
Begitu pula bagi mereka yang baru bermukim tanpa hubungan historis dengan wilayah hutan, tak bisa serta-merta mengklaim perlindungan putusan ini.
Implementasi di lapangan akan bergantung pada sejauh mana negara mampu memetakan dan mengakui keberadaan masyarakat adat. Hingga kini, dari sekitar 2.100 komunitas adat yang diidentifikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), baru sebagian kecil yang diakui secara hukum oleh pemerintah daerah maupun pusat.
—
Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial
Putusan MK ini membawa pesan moral yang tajam: keadilan sosial tidak boleh dikalahkan oleh legalitas administratif.
Selama ini, banyak konflik agraria lahir karena negara menempatkan izin dan sertifikat di atas sejarah dan budaya.
Di Riau, masyarakat Sakai menghadapi tumpang tindih antara lahan adat dan izin HTI.
Di Sulawesi Tengah, warga Kulawi menolak proyek hutan tanaman industri yang menggerus ruang hidup mereka.
Di Lampung Barat, masyarakat Semendo pernah terancam kehilangan tanah adatnya akibat klaim kawasan hutan produksi terbatas.
Kini, dengan keputusan MK, ada celah bagi penyembuhan sejarah: masyarakat adat punya dasar hukum untuk kembali menanam di tanah leluhur tanpa rasa takut — selama mereka menjaga prinsip non-komersial dan keberlanjutan lingkungan.
—
Penutup: Saatnya Negara Mengakui
Keputusan MK bukan akhir dari perjuangan, melainkan pintu masuk bagi reformasi agraria yang lebih manusiawi. Pemerintah perlu menindaklanjuti dengan kebijakan teknis — mulai dari peta wilayah adat, tata ruang kehutanan yang inklusif, hingga mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.
Masyarakat adat telah lama menjaga hutan tanpa izin tertulis; mereka hanya punya satu surat izin: izin dari sejarah.
Kini, setelah MK bicara, sudah sepatutnya negara berhenti memperlakukan penjaga hutan itu sebagai pelanggar.
Karena di dalam akar-akar pepohonan yang mereka rawat, tersimpan makna paling dalam dari Pasal 33 UUD 1945:
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
—
#MasyarakatAdat, #PutusanMK181, #HutanAdat ,#CiptaKerja, #KeadilanSosial, #TanahAdat, #KonflikAgraria, #ReformaAgraria, #HukumAdat, #HakAsasiPetani, #IndonesiaHijau,